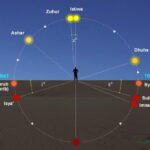JANGAN MAU SEPERTI KAMBING: Refleksi tentang Makna Hidup yang Terlupakan
Apa arti kemajuan ilmu pengetahuan jika ia hanyalah tumpukan data yang tak menyentuh jiwa? Apa arti rasionalitas tanpa kehadiran nurani yang membimbingnya? Kebenaran sejati bukanlah sekadar hasil akhir, melainkan perjalanan yang dijiwai oleh iman. Tanpa itu, pencarian kita hanyalah lingkaran kosong: ilmu untuk ilmu, seni untuk seni, hidup untuk sekadar hidup. Bagai pelaut yang mengarungi samudra tanpa kompas, kita mungkin sampai di pulau, tetapi tetap tersesat dalam makna.
Sekolah menjadi ritual pragmatis: nilai demi ijazah, ijazah demi gelar, gelar demi pekerjaan. Lalu, apa yang tersisa setelah semua capaian itu? Rumah, mobil, gawai—simbol-simbol yang kita puja sebagai bukti “keberhasilan”. Tapi di balik tumpukan materi, jiwa kita merintih: adakah arti lebih dalam dari sekadar bertahan hidup? Ketika kebaikan kita lahir dari kelebihan harta, bukan dari kerendahan hati, bukankah kita telah mengubur kemanusiaan dalam kubangan transaksi?
Kekayaan tanpa iman adalah perahu yang mengapung di atas lautan nihilisme. Halal dan haram diabaikan, asal keluarga terhidupi, anak tersekolahkan. Tapi lihatlah: di ujung jalan itu, koruptor merajalela, memakan bangsa sendiri. Mereka mungkin disebut “sukses”, tetapi di mata langit, mereka hanyalah pengemis yang menyembah angka—manusia yang menukar martabatnya dengan emas.
Kambing hidup untuk makan, kawin, dan mati. Manusia yang terjebak dalam lingkaran serupa—mencari, memiliki, lalu mati—apakah berbeda? Bahkan lebih hina: kambing tak punya pilihan, sedangkan manusia memilih untuk menyia-nyiakan akal dan kalbunya. Kambing mati menjadi sate, manusia mati meninggalkan warisan: apakah hanya debu, atau jejak abadi yang mencerahkan?
Seribu kambing ditambah seribu kambing tetaplah kambing. Mereka takkan pernah bertanya, “Mengapa aku ada?” Mereka takkan memberontak pada takdir. Tapi manusia? Kita bisa melampaui batas, merengkuh langit, mencipta makna. Namun, jika kita memilih untuk hidup dalam kandang nafsu duniawi—makan, tidur, beranak-pinak—bukankah kita sengaja merendahkan diri menjadi makhluk yang lebih rendah dari kambing?
Kita bukanlah makhluk yang ditakdirkan untuk sekadar ada. Setiap hela nafas adalah undangan untuk menjadi. Iman adalah lentera yang membebaskan kita dari kegelapan hedonisme. Ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh—tetapi ketika keduanya bersatu, kita menemukan tujuan sejati: mengabdi, mencintai, dan meninggikan derajat kemanusiaan.
Seribu tahun lagi, kambing tetap kambing. Tapi manusia—kita punya kuasa untuk menentukan: mati sebagai fosil yang terlupakan, atau hidup sebagai cahaya yang abadi. Pilihlah! Apakah kita akan tetap betah dalam kandang keserakahan, atau merobek belenggu itu, lalu berdiri tegak sebagai manusia seutuhnya—yang berpikir, beriman, dan berkarya untuk sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri? Ingat, hanya dalam iman dan amal yang ikhlas, kita menemukan jawaban: Kita bukan kambing. Kita adalah manusia—khalifah yang diamanahkan untuk memakmurkan bumi.